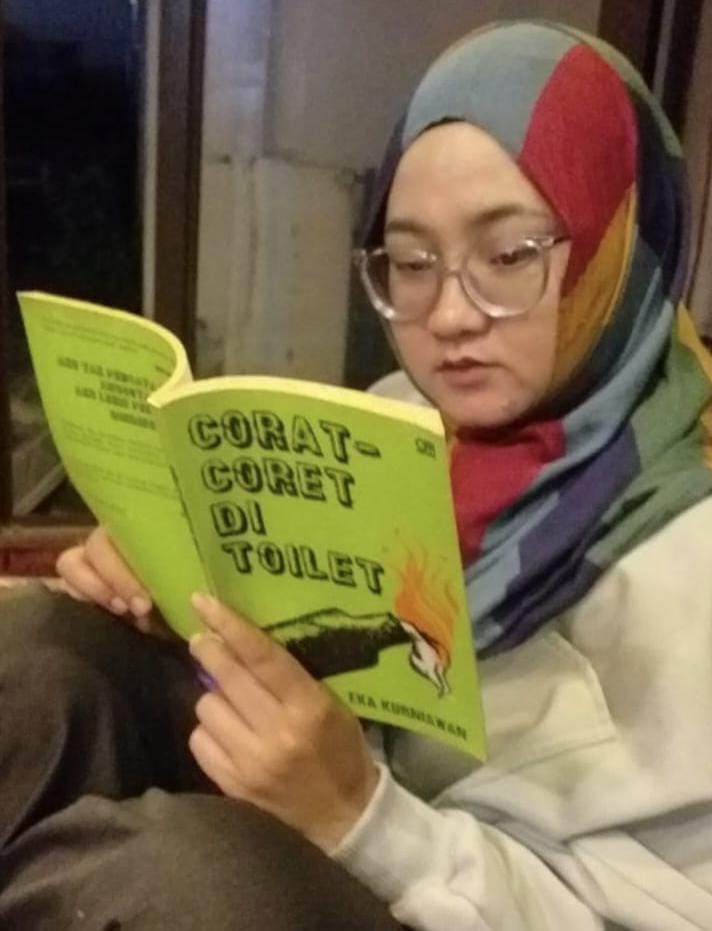Bayangkan Anda memiliki pohon yang menghasilkan uang di halaman rumah sendiri, tetapi Anda tidak boleh menyentuhnya. Orang dari luar kampung yang justru boleh
memanennya. Perasaan apa yang akan muncul? Kekecewaan? Kemarahan? Inilah
kenyataan pahit yang dialami oleh para petani hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Mereka menyaksikan setiap hari kekayaan getah pinus dari hutan yang mereka jaga
dikeruk oleh sebuah paguyuban yang mengatasnamakan konsosorium kelompok Tani Hutan, namun Sebagian besar penyadapnya dari luar daerah (Majenang), sementara akses mereka justru dibatasi. Situasi ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga
sebuah paradoks kebijakan. Di satu sisi, pemerintah punya aturan yang mulia untuk
memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Di sisi lain, di lapangan, yang terjadi adalah
praktik yang justru meminggirkan mereka.
Akar masalahnya kompleks, tetapi bisa diurai. Pertama, ada “pembiaran” yang
sistematis dari pengelola TNGC terhadap dominasi pihak ketiga ini. Kedua, suara
masyarakat lokal seperti hilang dalam gema kebijakan; mereka didengar, tetapi tidak
benar-benar didengarkan. Yang ketiga dan paling krusial, TNGC belum memiliki model
pemberdayaan yang jelas dan berpihak pada lokal. Padahal, contoh sukses sudah ada:
di Taman Nasional Halimun Salak, petani lokal mengelola getah pinus mereka sendiri
secara mandiri, tanpa perantara, dengan hasil yang lebih sejahtera dan hutan yang tetap terjaga.
Lantas, di mana letak persoalan hukumnya?
Secara hukum, posisi masyarakat lokal sebenarnya sangat kuat. Peraturan Menteri LHK No. 43 Tahun 2017 dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat sekitar kawasan adalah subjek utama pemberdayaan. Mereka yang hidupnya bergantung pada hutan itulah yang harus diutamakan dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK),
termasuk getah pinus. Praktik yang terjadi di TNGC saat ini jelas melenceng dari amanat
hukum tersebut dan berpotensi memicu konflik tenurial baru, mengulang kisah kelam seperti yang pernah terjadi di Cisantana dulu.
Lalu, apa solusi yang ditawarkan?
Kami percaya solusinya terletak pada pemberian kedaulatan penuh kepada
kelembagaan lokal. Berikut langkah-langkah konkret yang harus segera diambil oleh
Balai TNGC:
1. Alihkan Akses, Kembalikan Kedaulatan: Akses legal pengelolaan getah pinus
harus dialihkan dari paguyuban eksternal kepada Kelompok Tani Hutan (KTH)
lokal yang berkolaborasi dengan BUMDes atau Koperasi Desa. Ini adalah
implementasi nyata dari amanat hukum.
2. Perkuat Pilar Ekonomi Desa: BUMDes dan Koperasi bukan sekadar pengganti
paguyuban. Mereka adalah pilar baru untuk kemandirian ekonomi desa. Dengan
badan hukum yang jelas, mereka dapat mengelola keuangan secara transparan,
melakukan pemasaran kolektif yang lebih kuat, dan mendistribusikan keuntungan
secara adil. Uang akan berputar di dalam desa, memakmurkan warga sendiri.
3. Tiru yang Baik, Adaptasi yang Perlu: TNGC tidak perlu mulai dari nol. Model
pemberdayaan dari Taman Nasional Halimun Salak sudah terbukti berhasil.
Pelajari, adopsi, dan adaptasi model tersebut dengan melibatkan BUMDes/Koperasi sebagai pengelola utama.
4. Awasi Bersama, Jaga Bersama: Bentuk sistem pemantauan partisipatif yang
melibatkan Balai TNGC, BUMDes, dan KTH. Dengan begitu, tidak hanya
ekonominya yang adil, tetapi kelestarian hutan juga terjaga karena masyarakat
yang menjadi penjaga utamanya.
Kesimpulannya, pilihan bagi Balai TNGC sekarang sangat jelas.
Apakah akan terus membiarkan kebocoran ekonomi dan memelihara bibit konflik, atau
memilih untuk berdiri di sisi rakyat dengan membangun kedaulatan ekonomi mereka?
Momentum untuk memperbaiki kebijakan ini sudah sangat mendesak. Tindakan tegas
dan pro-lokal bukan hanya akan meredam konflik, tetapi akan mewujudkan trisula
manfaat: masyarakat sejahtera, ekosistem terjaga, dan stabilitas sosial kokoh. Saatnya
rakyat menguasai kembali getah pinus dari hutan mereka sendiri. Waktu untuk bertindak adalah sekarang.
Penulis
R Diah Ayu P
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kuningan, Aktivis lingkungan Hidup, advokasi masyarakat lokal dan pembangunan
berkelanjutan.